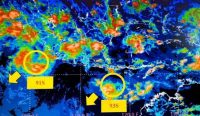Perempuan dan Narasi Kesetaraan
Athik Hidayatul Ummah, M.Pd., M.Si*
Dosen Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
KORANNTB.com -Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) telah kita peringati pada tanggal 8 Maret. Ini sebagai momentum peluh perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dan hak-haknya. Sebagai bahan refleksi, gagasan tentang peringatan ini diserukan untuk pertama kali di tengah gelombang industrialisasi dan ekpansi ekonomi pada abad ke-20. Sekitar tahun 1908, puluhan ribu buruh perempuan bergerak mewarnai jalanan memprotes kondisi kerja yang menyengsarakan dan menuntut upah yang lebih baik. Mereka juga menuntut hak berpendapat dan berpolitik. Melalui dinamika yang panjang, akhirnya diresmikan oleh PBB pada tahun 1975.
Adapun tema IWD tahun 2020 adalah “each for equal”. Kampanye ini penting untuk menyatukan pandangan dan gerakan bahwa setiap orang dapat menciptakan dunia yang adil dan setara. Mengutip statemen Gloria Steinem, “perjuangan perempuan untuk kesetaraan bukan hanya milik kaum feminis atau sekelompok orang saja, melainkan pada upaya kolektif semua orang yang peduli tentang hak asasi manusia”. Sementara sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer berpetuah, bahwa “kita harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Artinya, setiap ucapan, tindakan, pola pikir individu dapat berdampak pada masyarakat luas. Setiap orang dapat membantu menciptakan dunia yang setara. Karena kesetaraan ini bukan hanya masalah perempuan. Dunia yang setara dapat lebih sehat dan harmonis.
PBB memaparkan satu dari tiga perempuan menghadapi kekerasan di masa hidupnya. Setidaknya 740 juta perempuan mencari nafkah di sektor informal. Mereka memiliki akses yang terbatas atas perlindungan sosial maupun layanan publik. Kesenjangan gaji masih dirasakan, tenaga perempuan dibayar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Infrastruktur pun kadang luput dirancang dengan mempertimbangkan mobilitas dan keselamatan perempuan. Menurut WEF (World Economic Forum) setidaknya membutuhkan waktu 108 tahun untuk meniadakan kesenjangan gender di dunia ini.
Di Indonesia, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2020 bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.471 kasus. Jika dibandingkan dua belas tahun yang lalu, jumlahnya melonjak drastis dari 54.425 kasus (2008). Kasus kekerasan ini bak fenomena gunung es. Artinya, data yang dipaparkan adalah data yang dilaporkan. Sementara banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, misalnya takut, malu, dsb. Situasi tersebut juga bermakna bahwa perlindungan dan keamanan perempuan masih jauh dari harapan.
Sementara menurut P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) NTB, tercatat 1.679 kasus kekerasan (2016) dan meningkat 1.821 kasus (2017). Dari semua kasus yang terjadi, sekitar 70% yaitu kasus inses atau kekerasan seksual dimana pelaku dan korban memiliki ikatan keluarga yang dekat. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk: fisik, seksual, verbal, ekonomi, dll. Kekerasan juga terjadi di hampir semua domain, di ruang private maupun public. Terjadi di lingkungan keluarga, komunitas, maupun tempat kerja. Dilakukan oleh orang terdekat maupun tak dikenal.
Era digitalisasi menyebabkan ruang aman bagi perempuan semakin terusik. Fenomena kejahatan siber semakin marak dan menyasar pada perempuan sebagai obyek korban. Bentuk kejahatan siber bisa berupa ancaman maupun intimidasi penyebaran foto atau video porno. Bahkan kekerasan terhadap perempuan difabel juga semakin banyak. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang kesetaraan di masyarakat masih rendah. Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan kelas dua (subordinat). Inilah yang menyebabkan relasi tidak seimbang.
Sebagian masyarakat masih memegang teguh wilayah kerja perempuan hanya seputar “dapur, sumur, kasur”. Kerja-kerja domestik selalu dibebankan hanya kepada perempuan. Alhasil perempuan mendapatkan akses pendidikan yang terbatas, lantas tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itulah mengapa kemiskinan seringkali berwajah perempuan. Berdasarkan data World Bank (2018), pendidikan di Indonesia pada masyarakat kelas bawah menunjukkan perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, yang menyelesaikan pendidikan menengah yaitu 44% laki-laki dan 37% perempuan. Partisipasi bekerja laki-laki mencapai 82%, sementara perempuan hanya 52%. Alih-alih bisa setara, akhirnya perempuan memiliki ruang yang lebih sempit untuk berperan dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Pertanyaan yang sering muncul dalam diskursus tentang perempuan, “mengapa ketidakadilan gender selalu ada, bahkan cenderung makin meluas?” Ketidakadilan gender nyatanya menyelimuti hampir setiap perempuan di belahan dunia ini. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan kepekaan masyarakat baik secara individu maupun kolektif.
Masyarakat yang memandang bahwa kondisi ini adalah wajar, maka mereka akan menerima dengan pasrah. Sebagian kelompok masyarakat lain memandang bahwa ketidakadilan hadir sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya yang berlaku. Maka dibutuhkan upaya untuk mengubah struktur dan budaya yang lebih egaliter, adil, dan demokratis. Ini bisa terealisasi dengan melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
Menurut data BPS 2018, jumlah perempuan ‘setara’ 50,1% dengan laki-laki. Oleh karenanya eksistensi perempuan penting sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Nyatanya, perempuan belum dapat optimal menyumbangkan potensi dan kemampuannya akibat ketimpangan, ketidakdilan, dan ketidaksetaraan yang terjadi. Pengalaman berbicara bahwa tidak ada solusi tunggal dan mudah untuk menghapus ketidakadilan gender. Hal ini muncul karena berbagai faktor yang saling berkelindan. Misal, faktor budaya, penafsiran nilai-nilai agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarkat, atau bahkan produk hukum dan kebijakan publik yang bias gender.
Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yaitu pendekatan struktural dan kultural. Pertama, pendekatan struktural dapat melalui penguatan institusi/lembaga, penegakan hukum, kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang memastikan adanya keadilan gender dan penghapusan diskriminasi. Hal itu bisa dijabarkan dalam aksi nyata. Misal: meningkatkan akses perempuan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja, meningkatkan kualitas kesehatan dan reproduksi perempuan, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak, mencegah perkawinan anak, trafficking/perdagangan perempuan, dsb.
Kedua, pendekatan kultural dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, merekonstruksi nilai-nilai budaya dan reinterpretasi teks-teks dan tafsir agama yang ramah terhadap perempuan dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran agama harus paling depan menjadi benteng pertahanan manusia, khususnya perempuan dari perlakuan diskriminasi, ketidakdilan, maupun kekerasan.
Sesungguhnya Islam telah memproklamirkan keutuhan kemanusiaan, bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Keduanya sama-sama ciptaan allah, sama-sama manusia, dan berpotensi menjadi khalifah fil ardh. Karena itu, tugas keduanya adalah ber-fastabiqul khairat (berkompetisi melakukan amal-amal shaleh) demi meningkatkan kualitas takwanya (QS. Al-Hujurat: 49).
Dalam Al-Qur’an, figur muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik seperti ratu Bilqis yang memimpin kerajaan superpower (QS. An-Naml:27), serta figur-figur perempuan tangguh lainnya. Pun di masa Rasulullah, sejumlah perempuan memiliki prestasi dan kemampuan yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat: politik, ekonomi, dan sektor publik lainnya.